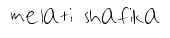Ahmad
Hardi duduk menghadap meja makan sambil memerhatikan isterinya menyediakan
hidangan lewat malam itu. Anak-anak mereka sudah lama tidur. Cuma dia yang
lewat balik.
“Ami,
duduklah sebentar. Abang ada benda nak cakap dengan Ami.”
“Ye,
abang. Kejap ek, biar Ami bancuh air panas ni dulu,”
Hati
Ahmad Hardi sudah tidak keruan. Lagi lama dia menyimpan rahsia itu, lebih
bersalah dia rasa untuk berhadapan dengan isterinya.
“Ami,
abang nak kahwin lain.”
Naziffa
Amira terdiam. Tangannya yang tadi lincah terhenti seketika. Nafasnya turun
naik. Dia cuba mengatakan apa yang didengarnya itu tidak benar.
Ahmad
Hardi masih menunggu reaksi isterinya. Rambutnya dikuak perlahan. Dia
terbayangkan wajah Farah Adrianna. Wanita yang baru-baru ini muncul mencuri hatinya.
“Betulkah
abang?” Naziffa Amira cuba bersuara seperti biasa walaupun hakikatnya hatinya
ketika itu bagai ditusuk sembilu.
Ahmad
Hardi tersentak. Wajah kekasih hatinya segera hilang dari ingatan. Dia menatap
pula wajah isterinya yang jelas kelihatan cuba menyembunyikan rasa sedihnya.
“Abang
nak kahwin lain?” tanya Amira semula sayu. Teh suam yang dibancuh untuk
suaminya tadi diletakkan di atas meja.
Suaminya
mengangguk mengiyakan.
Amira
diam lagi, tidak tahu apa yang harus dikatakan pada suaminya. Dia meneguk air
liur. Sesungguhnya dia hilang kata-kata. Berita itu agak sukar untuk dicernakan
ke dalam mindanya.
“Nanti
Amira fikirkan.” Akhirnya itu yang keluar dari dua ulas bibirnya.
“Ami..”
“Abang
minumlah dulu, Ami nak tidur.” Segera Amira bangun menuju kamar tidur anaknya
yang paling bongsu.
Amira
baring di sebelah anaknya. Dia menghela nafas panjang. Tubuh kecil anaknya yang
baru menjangkau dua tahun itu dipeluk. Rasa sebak tiba-tiba hadir menghuni
seluruh jiwa. Tanpa disedari, air matanya mengalir laju. Dia menangis. Hatinya
pilu. Hatinya sudah terhiris, tersayat dan hancur. Kenapa ini yang berlaku?
Kenapa harus aku yang melalui semua ini? Selama ini aku cuma mendengar
cerita-cerita sebegini. Kini, aku pula… Ya Allah, hebat betul ujian yang
terpaksa aku tempuh ini. Kau tabahkanlah aku untuk menghadapi dugaan ini. Amira
menghela nafas. Berat. Ya Allah, aku mohon padaMu berikanlah aku kekuatan agar
aku mampu menempuh kesukaran ini.
***
Ahmad
Hardi sedang bersiap- siap untuk ke tempat kerja bila isterinya muncul dari
dapur.
“Kenapa
Ami tak siap lagi? Ami tak kerja hari ini?”
“Abang
dah lupa? Bukan Ami dah bagitahu abang minggu lepas, Ami cuti. Eimran kan ada appointment dekat klinik hari ni?”
“Oh!
Abang lupa.”
Macam
manalah nak ingat, kalau tengah hangat bercinta. Ingin sahaja Naziffa Amira
berkata begitu tapi dibiarkan sahaja kata-kata itu terngiang-ngiang di kotak
mindanya.
“Ami
boleh pergi seorang?”
Naziffa
Amira mengangguk sebelum mencium tangan suaminya.
“Abang
pergi dulu,” ujar Ahmad Hardi ketika mahu bertolak ke tempat kerja.
Naziffa
Amira memandang sahaja suaminya yang kelihatan bersemangat. Mungkin kerana dia
akan bertemu dengan kekasih hatinya hari ini. Naziffa Amira mengeluh dan air
matanya menitis lagi.
***
Lama
Naziffa Amira bermenung. Memikirkan kalau-kalau ada kekurangan dalam hubungan
dia dan Ahmad Hardi. Hubungan yang bersatu atas dasar cinta dan restu kedua
belah keluarga.
Bermasalahkah
rumah tangga aku? Rasa macam tidak ada cacat-celanya hubungan mereka selama
ini. Jarang ada pertelingkahan. Jadi di manakah silapnya?
Apa
aku sudah tidak cukup menarikkah di mata suami aku? Di pandang wajah dan tubuh
badannya di hadapan cermin. Teringat akan kata-kata teman sepejabatnya.
“Engkau
dah ada anak dua. Umur dah masuk 35 tahun tapi masih macam anak dara. Aku yang
sebaya dengan kau ni pula dah nampak macam makcik-makcik.”
Dia
tertawa mendengar bicara Harlina itu. “Ada-ada je kau ni.”
“Betul..apa
rahsia engkau? Petua ker? Kongsi-kongsilah.”
“Mana
ada apa-apa rahsia pun.”
Naziffa
Amira mengeluh. Hendak dikatakan zuriat puncanya, anaknya yang sulung kini
sudah berumur 10 tahun. Perempuan. Yang kedua pula lelaki. Sepasang. Kalau
Ahmad Hardi nak menambah lagi keturunannya, dia juga tidak pernah membantah.
Tidak pernah pula suaminya itu mewar-warkan yang dia kepingin untuk menimang
cahaya mata lagi.
Selama
ini aku terlalu memintakah? Sehingga dia tidak mampu memenuhi segala permintaan
aku. Seingat-ingat aku, jarang sekali aku meminta dibelikan harta benda.
Perhiasan wanita mahupun aksesori. Barang kemas yang dipakai selama ini, adalah
hadiah perkahwinannya. Tidak pernah dia menggantikannya. Tidak terlintas di
hati.
Atau
independent sangatkah aku sehingga
dia merasa dirinya tidak diperlukan dalam hidup aku? Mungkinkah begitu? Independent sangatkah aku?
Ya,
aku bekerja, aku ada duit gaji aku sendiri dan jarang mengharap hasil titik
peluhnya. Aku bersyukur kalau dia memberi tapi selama ini dia tidak pernah
menghulur duit gajinya pada aku melainkan kalau aku meminta. Malangnya, aku
jarang sekali meminta. Tapi itu tidak bermakna aku mengetepikan dia. Tidak,
cuma aku merasakan dia sebagai ketua keluarga, dia tahu tanggung-jawabnya. Aku
tidak perlu mengingatkan dia.
Semuanya
aku berkongsi dengan dia. Aku dengar pendapat dia. Aku pertimbangkan baik dan
buruk sebelum membuat sebarang keputusan. Jadi di mana silapnya aku?
Sebelas
tahun usia perkahwinan mereka. Sebelas tahun dia setia di sisi suami, di kala
duka di kala suka. Ini yang dia dapat? Tidak cukupkah segala pengorbanan yang
telah dia lakukan? Naziffa Amira sebak.
Argh!
Mungkin sudah takdir dia jatuh cinta lagi. Masalahnya sanggupkah aku bermadu? Kalau
tidak, sanggupkah aku berpisah? Bagaimana pula dengan anak-anak nanti? Akan
mengikut aku atau mengikut ayah mereka. Kalau aku memilih untuk bermadu pula, relakah
aku?
Tamakkah
aku kalau aku menginginkan suami aku untuk diri aku sendiri. Ya Allah, kalau
benar begitu jauhkanlah aku dari sikap yang sebegitu. Aku tidak pernah mahu
berniat seperti itu.
Begitu
banyak persoalan bermain di mindanya ketika itu. Naziffa Amira memicit dahinya.
Mungkin
benar suami bukan hak mutlak isteri. Tapi, isteri hak mutlak suami? Tidak, aku tidak
fikir begitu. Haish!
Mungkin
aku yang tidak cukup sempurna. Mungkin aku yang gagal memberi kebahagiaan yang
sepenuhnya kepadanya sehingga dia sanggup mencari kebahagian itu dari perempuan
lain?
Kalau
benar kenapa tidak berbincang sahaja? Bukannya sukar pun untuk berbincang
dengan aku. Aku sedia sahaja untuk memperbaiki segala kekurangan aku.
Atau
memang mungkin dia benar-benar sudah jatuh hati pada perempuan lain. Kalau
sudah begitu, mungkin cintanya pada aku sudah pudar. Mungkin masanya bersama
aku setakat ini sahaja. Masa dia untuk bahagia bersama aku sudah berakhir. Atau
mungkin juga masa aku untuk dia sudah tamat tempohnya. Mungkin aku juga perlu
mencari kebahagiaan lain?
Ya
Allah, tunjukkanlah jalan kepadaku. Mudah-mudahan ada hikmah di sebalik semua
ini. Naziffa Amira meraup wajahnya. Dia tidak mahu berfikir lagi. Kepalanya
sakit, hatinya masih terluka. Hendak mengadu, suaminya sudah berpaling pada
yang lain.
***
“Sabar
betul engkau ni Amira. Kalau aku, dah lama aku melenting,” terangkat-angkat
kening Harlina menyuarakannya.
“Apapun
aku bersyukur, dia memberitahu terlebih dahulu. Sia tidak menyembunyikan
kebenaran itu dari aku,” Naziffa Amira tersenyum pahit.
Harlina
pandang sahabatnya itu semacam. Boleh tersenyum lagi, fikirnya. Dia
menggelengkan kepala. “Habis tu kau setuju dia kahwin lagi?”
“Entahlah
aku tak tahu.Kalau aku tak setuju pun, mungkin dia akan cari jalan lain. Kahwin
kat sempadan maybe?”
“Kau
macam tak kisah je.”
“Dah
kering air mata aku Lina. Kalau aku menangis air mata darah sekalipun, ianya
mungkin tidak akan mengubah apa-apa.”
“Erkk…”
“Daripada
aku meratapi nasib aku, lebih baik aku fikirkan yang terbaik untuk keluarga
aku.”
“Amira,
aku tak tahu nak kata apa tapi aku sungguh-sungguh bersimpati dengan engkau.”
“Me too..” balas Amira perlahan.
“Aku
tak tahu macam mana nak bantu engkau.”
“Kau
sudah cukup membantu aku, Lina. You lend
me your ears. You are a good listener and I am very grateful to have you as a
friend.”
Harlina
memeluk bahu Naziffa Amira. Kalau aku berada di tempat kau, tidak mungkin aku
boleh jadi setabah engkau. Bisiknya dalam hati.
***
“Ami
tak membantah.”
Terbata-bata
Ahmad Hardi mendengar, mungkin kerana tidak percaya yang isterinya itu akan berkata
begitu.
“Kalau
abang nak kahwin lagi, Ami tidak ada halangan.”
“Betulkah
ni? Betulkah sayang?”
Sayang?
Naziffa Amira tersenyum lirih, masih ada lagikah rasa sayang itu? Kalau masih
ada, kenapa mahu menikah lagi satu? Tapi kata-kata itu bagai tersekat di
kerongkong. Ditahan air mata yang ingin tumpah.
“Sayang
tak nak tanya kenapa?” Mata Ahmad Hardi tepat pada isterinya itu. Masih agak
terkejut dengan kata-kata isterinya.
Naziffa
Amira membalas pandangan itu begitu saja.
“Sayang
tak nak bagi abang syarat?” tanya suaminya lagi.
Untuk
apa bersyarat-syarat lagi kalau dalam
hati sudah ada orang lain bertakhta di hati. Naziffa Amira menggeleng-gelengkan
kepala. Dia ingin berlalu dari situ secepat yang boleh. Dia takut dia tidak
mampu menghadapinya. Dalam keadaan teragak-agak dia bersuara.
“Terlanjur
abang bertanya, Ami tiada sebarang syarat, Cuma kalau sudah tidak ada rasa
kasih abang pada Ami, lepaskan Ami secara baik.” Dia tahu permintaan itu
sesuatu yang dimurkai yang maha Esa tapi rasanya dia tidak rela menanggung hati
yang mungkin terdera dengan rasa terseksa kelak.
“Ami…”
hanya itu yang keluar dari dua ulas bibir Ahmad Hardi. Agak terkedu dengan
permintaan isterinya.
Pantas
Naziffa Amira berlalu pergi, hatinya sedih. Sedih yang amat. Dia mahu menangis
tapi bukan di hadapan orang yang sudah tidak mencintainya lagi.
***
Hari-hari
yang berlalu dijalani seperti biasa. Ahmad Hardi pandang isterinya yang sedang
tekun menyediakan makan malam. Isterinya masih melayannya seperti biasa.
Aku
sepatutnya gembira kerana dia sudah bagi green
light tapi kenapa aku tidak rasa begitu?
“Abang,
Ami nak balik kampung. Seminggu.”
Ahmad
Hardi tersentak. “Ok. Bila?”
“Esok.
Ami dah ambil cuti.”
“Esok?
Abang ikut sekali?”
“Tak
apa, Ami nak balik seorang. Abang tolong jaga anak-anak.”
“Betul
ni? Sayang okey tak?”
Naziffa
Amira tergelak. Apa yang suaminya sedang fikirkan? “Takkanlah abang tak kenal Ami.
Ami tak akan buat perkara-perkara yang macam itulah.”
Ahmad
Hardi tersenyum malu.
“Abang?”
“Hmm?”
“Siapa
nama dia?”
“Siapa?”
“Nama
perempuan yang menggantikan tempat Ami di hati abang?”
Ahmad
Hardi teguk air liur. Serba-salah. “Err..”
“Tak
apalah, kalau abang tak mahu bagitahu. Saja Ami bertanya.”
“Farah.
Farah Adrianna.”
Naziffa
Amira diam sejenak. “Cantik namanya. Ami pasti orangnya juga secantik namanya.”
Ahmad
Hardi tersenyum pahit. Agak kelu untuk bersuara.
“Dia
tahu abang sudah berkahwin?”
Ahmad
Hardi mengangguk. Memang dia ada memberitahu Farah Adrianna yang dia sudah
beristeri dan mempunyai dua orang anak.
“Patutkah
Ami bertemu dengan dia?”
Wajah
Ahmad Hardi bertukar riak. Ingin sahaja dia bertanya, apa perlunya? Tapi Amira
terlebih dahulu bersuara.
“Ami
fikir, tidak perlulah. Lagipun, kita akan berpisah jua akhirnya. Sebaiknya
abang jagalah dia lebih baik dari abang jaga Ami.”
Ahmad
Hardi senyap dan hatinya mula gusar. Berpisah?
***
Wajah
isterinya yang sedang tidur nyenyak ditatap. Wajah itu masih kelihatan manis
seperti dulu. Dia tersenyum bila teringatkan detik pertama perkenalan mereka.
Betapa susahnya dia hendak memiliki Naziffa Amira. Kini dengan mudahnya dia
ingin melepaskan.
“Ami
tak minta apa pun, cukuplah abang jaga hati Ami dengan sebaiknya. Ami tak nak
harta kekayaan itu semua. Ami bersyukur kalau abang sudi menerima Ami
seadanya.”
Teringat
dia akan janjinya pada Naziffa Amira. “Abang tak ada harta nak offer kat Ami, cuma kasih sayang sahaja
yang mampu abang berikan.”
“Ami..”
bisiknya perlahan.
Naziffa
Amira yang bagai terdengar suaminya menyebut namanya membuka kelopak mata.
Dalam keadaan yang masih mamai dia bersuara. “Kenapa ni bang? Abang tak tidur
lagi?”
“Maafkan
abang, sayang.” Dahi isterinya dikucup.
“Abang?”
“Abang
cintakan sayang. Cuma abang terleka seketika. Sayang maafkan abang kan?”
Naziffa
Amira tersenyum dalam keadaan separuh sedar. Apalah suami aku merepek ni? “Abang
tak ada salah pada Ami pun. Tidurlah..”
Ahmad
Hardi melepaskan sebuah keluhan. Dia baring di sebelah isterinya. Dipeluknya
tubuh isterinya itu. Hatinya masih gusar. Wajarkah dia melepaskan isterinya itu
sedangkan dia masih lagi mencintainya? Bagaimana pula dengan Farah Adrianna?
***
Seorang
wanita melangkah masuk ke pejabat Naziffa Amira diriingi oleh penyambut tetamu.
“Awak
siapa?” tanya Naziffa Amira.
“Saya
Farah Adrianna.”
Dahi
Naziffa Amira berkerut bila mendengar nama itu. Inilah perempuan itu. Perempuan
yang berada di sisi suamiku.
“Silakan
duduk Cik Farah.”
Lama
mereka terdiam.
“Kenapa
awak nak bertemu dengan saya?” Akhirnya Naziffa Amira membuka mulut terlebih
dahulu.
“Just out of curious,” balas Farah
Adrianna sambil memandang Naziffa Amira yang kelihatan tenang-tenang sahaja.
“Curious?” Bukan sepatutnya aku yang
berfikiran begitu?
“Awak
tak pernah terfikir nak bertemu dengan saya ke?” soal Farah Adrianna.
“Bohonglah
kalau saya katakan tidak terdetik di hati saya untuk mengetahui siapa perempuan
itu, yang bakal hidup di samping suami saya.” Hendak dikatakan perempuan
perampas, tidak sampai pula hati Naziffa Amira. Mungkin sahaja perempuan itu
tidak bermaksud untuk merampas suaminya.
“Kenapa
awak benarkan suami awak berkahwin lagi?”
“Kalau
suami saya bakal beroleh kebahagiaan dengan berkahwin dengan awak, kenapa saya
harus menghalang? Lagipun, apa kesudahannya kalau saya menghalang? Mungkinkah
ia akan jadi lebih baik untuk saya?” Naziffa Amira pandang wajah perempuan itu.
Nampak macam orang baik-baik sahaja. Mungkin dia boleh jaga suami aku lebih
baik daripada aku.
“Tapi,
awak tidak ingin bersama dengan dia lagi lepas dia menikah dengan saya.”
Naziffa
Amira tersenyum. “Saya tidak mahu dia berbelah bagi. Saya tidak mahu kelak saya
bakal menjadikan dia seorang suami yang tidak berlaku adil, seandainya saya
masih lagi menjadi isterinya ketika itu.”
“Awak
meragui dia?”
“Bukan
begitu. Saya meragui diri sendiri. Saya tidak fikir saya mampu.menghadapi
kehidupan begitu. Saya mungkin tidak kuat melawan rasa cemburu yang lahir. Saya
mungkin akan jatuh berdosa kalau kelak saya tidak mampu menerima kenyataan yang
suami saya mempunyai seorang lagi isteri yang harus dijaga makan-minumnya. Yang
harus ditunaikan hak nafkah zahir dan batinnya. Saya tidak juga mahu kelak saya
jadi madu yang menyekat kebahagiaan dan kenikmatan hidup berkeluarga suami dan
isterinya yang baru.”
Naziffa
Amira berhenti sejenak sebelum meneruskan. “Saya tidak berharap awak faham.
Tapi, sepertimana saya menghormati keinginannya untuk mendirikan rumah tangga
dengan awak, seperti itu jugalah saya mohon agar dia menghormati pilihan saya
untuk tidak terus bersama dengan dia. Mungkin itulah jalan yang terbaik untuk
kita semua.”
Farah
Adrianna tertunduk. Hatinya terusik mendengar penjelasan Naziffa Amira. Wajah
Naziffa Amira dipandang. Memang dia ingin bertemu dengan wanita itu. Dia mahu
tahu kenapa Ahmad Hardi membatalkan hasrat untuk meneruskan pernikahan mereka.
Dia mahu tahu apa hebatnya wanita itu berbanding dirinya.
“Awak
hebat.”
“Apa
maksud awak?”
“Just to let you know, we are not getting
married. Me and your husband, is not going to happen.” Ada air mata
bergenang kelihatan.
“Maafkan
saya,” balas Naziffa Amira agak terkejut dengan perkembangan itu. Di kala dia
betul-betul pasrah dengan ketentuan itu, di kala dia sudah bersedia menerima suratan
yang tertulis akhirnya kejutan itu yang diperolehinya.
“No, maafkan saya. I have should know better than to mess with other people life.
Specially, the one that already married.” Farah Adrianna tersenyum pahit.
Naziffa
Amira tidak terkata. Ada rasa sedih yang lahir buat Farah Adrianna, mungkin
perempuan itu benar-benar ikhlas mencintai suaminya. Tapi pada yang masa jauh
di sudut hati dia rasa bersyukur kerana perkahwinannya masih mampu
diselamatkan.
“I learnt my lesson.” Ucap Farah Adrianna
sebelum melangkah pergi.
Me too,
jawab Naziffa Amira dalam hati.
Mungkin
dugaan yang hadir itu bukan bertujuan untuk melumpuhkan diri tapi untuk menguji
tahap kesabaran dan cara terbaik menanganinya. Mungkin ia perlu untuk
mengingatkan diri supaya sentiasa bersedia menghadapi segala kemungkinan yang
terburuk dan bersyukur dengan apa yang kita ada selagi masih ada waktu. Renung Naziffa
Amira ketika mengimbas kembali apa yang telah berlaku.
***
Sejambak
bunga dihulurkan pada Naziffa Amira. Tidak pernah-pernah suaminya itu memberi
bunga kepadanya selama mereka berkahwin.
“Untuk
Ami?”
“Untuk
Ami. Tanda abang minta maaf.”
“Abang?
Kenapalah membazir beli semua ini.”
“Abang
tahu tapi untuk Ami, abang rasa ini sangat sedikit kalau dibandingkan dengan
apa yang telah Ami lakukan untuk abang, untuk keluarga. Sepatutnya abang buat
lebih.”
Naziffa
Amira sedikit tersentuh.
“Abang
hampir kehilangan Ami. Sepatutnya abang lebih tahu yang cinta Ami tidak
berbaloi untuk dikorbankan untuk apa-apa pun di dunia ini. Abang buta
menilainya.”
Ahmad
Hardi memeluk isterinya seperti tidak mahu dilepaskan apatah lagi bila
isterinya membalas pelukan itu. Terasa seperti sudah lama tidak merasa
kehangatan itu. “Terima kasih kerana masih mahu menerima abang. Abang akan cuba
jadi yang terbaik untuk Ami dan anak-anak kita.”